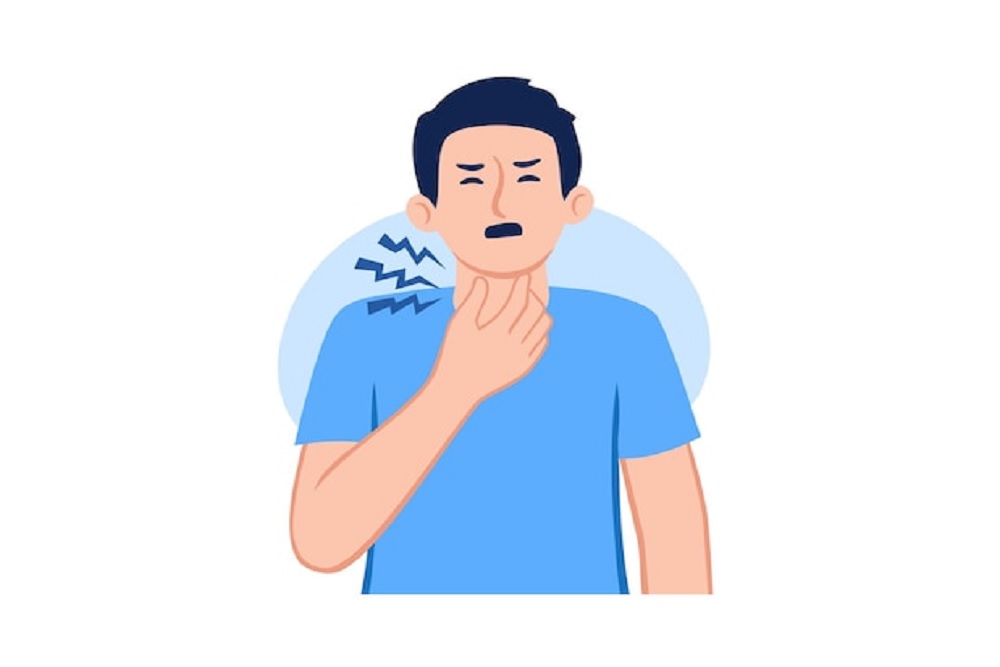Harusnya kujual saja rumah itu dengan harga murah. Atau lebih berhati-hati di lain kali.
Baru kali ini ada seseorang dengan sengaja menemuiku untuk menawarkan harga yang tinggi atas rumah almarhum Angku Badri di tepi kiri jalan setelah melewati jembatan surau sana. Padahal, aku tidak sekalipun berniat memindahalihkan rumah itu untuk dijual kepada siapa pun setelah ditinggal pemiliknya lima tahun lalu. Sebagaimana wasiat Ayah sebelum menyusul Angku, aku tidak boleh menjual rumah ini sampai orang itu tiba. Akan tetapi, pria paruh baya yang mengenalkan dirinya dengan nama Hendra Tanjung itu kini datang ke rumahku seorang diri, setelah mendapatkan alamat rumahku dari pak Wali Nagari.
“Karena kopi sudah terletak di atas meja. Tidak baik untuk dibiarkan terlalu lama, Da. Ini adalah kopi terbaik yang ditanam di lereng gunung Pasaman. Silakan!”
Kami berdua lalu menyeruput gelas masing-masing. Tak sampai lima detik, suara kepuasan akhirnya terucap. Dan proses tawar menawar pun kami lanjutkan.
“Rumah ini tidak untuk dijual, Da. Ahli waris almarhum belum menampakkan diri.”
“Tenang, Pak Jorong. Aku juga pernah belajar hukum sewaktu muda.”
Da Hendra hanya tertawa tipis. Dia juga mengataiku dengan sebutan bongak karena terlalu polos. Atau sebutan lainnya “orang yang tidak paham jika uang bisa memberikan kebahagiaan”. Menurutnya, apabila ahli waris sudah tidak ada, maka ia harus diberikan kepada lembaga wakaf atau yang bersangkutan.
“Tapi seperti yang kau tahu. Tidak salah juga, jika rumah itu kubeli saja darimu. Bukankah kau punya anak yang harus disekolahkan, Pak Jorong?” Lanjutnya.
“Sekali lagi aku katakan Hendra. Rumah ini masih memiliki ahli waris. Apa salahnya jika kau tunggu saja sampai ia tiba?”
Seketika, punggungku terasa lengket dengan baju karena keringat, aku mengatur napas dengan bantuan sedikit asap. Sebatang. Dua batang. Arang tembakau berkumpul di asbak perak aluminium.
“Oh, ya. Aku lupa menanyakan sesuatu, Pak Jorong. Siapa sebenarnya pemilik rumah itu? Kau sepertinya sangat mengenalinya.”
Aku mengulur sepuluh detik untuk berpikir sebelum bercerita. Ketika api tembakauku hampir menyentuh ibu jari.
Rumah itu dahulunya didiami oleh perantau dari Jawa. Kerasnya hidup di sana membuat Mas Badri bersama Mbak Rini memilih keluar dari kampung halaman lewat program transmigrasi dari pemerintah daerah Jawa Tengah. Dengan niat mengubah nasib, keduanya bekerja keras untuk hidup layak sebagai buruh sawit di kecamatan sebelah bersama tetangga.
Melalui cerita Ayah, kehadiran Angku Badri di kampung ini memang membawa suasana baru bagi pribumi. Sifatnya yang ramah dan tutur katanya yang merdu membuat telinga siapa pun betah. Apalagi saat ia diminta menjadi muazin, anak-anak mulai meramaikan surau kembali, walaupun ujung-ujungnya mereka tetap bermain saat orang dewasa akan rukuk dan sujud.
Lima tahun setelah kedatangannya akhirnya mendatangkan hasil. Setengah hektare sawah akhirnya bisa ia dapatkan setelah menabung dan membeli motor kongkor[i]. Kiranya, lahan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur bersama istrinya. Namun begitulah takdir datang. Teradang dengan kabar baik dan terkadang berbentuk tidak baik. Rini meninggal setelah jatuh dari kamar mandi. Dan sialnya, Rini belum bisa menambah panggilan baru untuk Badri.
Angku Badri pernah berusaha cukup lama untuk mendapatkan keturunan. Empat hari empat puluh malam bersuluk juga sudah beliau jalankan agar harapannya terkabulkan. Tapi takdir berkata lain. Barangkali hidup memang tidak seperti yang beliau inginkan.
Perhatianku kepada Angku Badri bertambah sepeninggal istrinya. Sebab, Ayah berteman baik dengan beliau saat masih menjadi kuli sawit. Ketika masa-masa awal bekerja, Ayah sering menjemput Angku Badri untuk pergi bekerja setiap pagi hari. Kecuali hari Jumat.
Sebab, sawahnya berdekatan dengan kolam pemancingan langganan kami bersama Ayah. Setiap Sabtu dan Minggu sore. Kami selalu menyempatkan waktu untuk memancing bersama. Ayah biasanya akan memberikan satu atau dua ikan Mas yang cukup besar kepada beliau jika hasil tangkapan cukup banyak.
“Apa yang kau pikirkan, Nak,” kata Ayah melihatku sedang termenung.
“Apa ada sesuatu yang terjadi dengan Angku Badri? Pandanganmu tadi cukup serius melihat dia mencangkul di sana.”
“Aku punya firasat aneh, Yah. Angku Badri sudah seminggu tidak mengumandangkan azan.”
Hendra kemudian memasang telinganya. Khidmat mendengarkan cerita.
Ketika itu, Mas Badri telah selesai dengan azan pertamanya. Tetapi Ustaz Arifin yang akan menjadi khatib permanen kelihatannya berhalangan untuk tiba. Maka dengan keputusan jamaah di saf pertama, Mas Badri diminta untuk menjadi khatib jika setelah dua rakaat, beliau tak kunjung tiba.
Khutbah pun akhirnya berlangsung dengan kejutan. Sosok yang dikenal lembut, ternyata bisa juga menjadi sangar. Entah apa ilmu yang dimilikinya. Mudah saja ia mengisi khutbah tanpa ada persiapan. Melihatnya saja sudah seperti seorang komandan Batalyon dibanding pengisi khutbah. Semua jamaah takjub atas pembawaan. Jamaah yang sudah bermimpi ingin beristri empat akhirnya gagal.
Tapi ada sedikit yang menjanggal. Untuk pertama kalinya, aku mendengar ada khatib yang menyampaikan perkara menjaga aib sesama saudara. Ayat al- Quran ia bawakan, riwayat hadis, ia bacakan.
“Lalu?” tanya Ayah dengan nada heran.
“Beliau menatapku dengan menekuk alisnya walaupun sesaat.”
“Bukannya seorang khatib memang lebih baik jika melihat jamaahnya dan sebaliknya?” tanya Ayah.
“Tapi kali ini berbeda, Yah. Matanya melotot seperti ikan. Bukan, seperti dendam.”
“Begitu ya.”
Ayah menatap umpannya dengan lama. Kadang aku berpikir, mungkin Ayah bisa melihat peristiwa lampau lewat bayangan dari pantulan air kolam. Umpan Ayah langsung bergerak, ia dengan sigap menarik mata kailnya.
“Ibumu pasti senang melihat ikan sebesar ini.”
Aku lalu membereskan barang-barang karena tarhim sudah terdengar.
“BADRIIII!!, AYO PULANG,” teriak Ayah dari kursi kecilnya yang berbahan plastik. Beliau lalu melambaikan tangannya dari jauh.
“Kami Tungguuu,” teriak Ayah.
Beliau lalu bersiap pulang. Dia menancap gas motornya, lalu menghampiri kami.
“Coba lihat Badri! Ini ikan yang kudapat,” kata Ayah sambil menunjukkan hasil kesabarannya.
Bukannya gembira, beliau seperti terlihat cemas melihat ikan-ikan yang akan kami makan nanti malam.
“Ambil ini!” tutur Ayah sambil memberikan ikan mas yang terakhir ia dapat.
Beliau menerimanya tanpa senyuman.
“Apakah kau bisa datang malam ini, Bahar?” Ayah terlihat tiba-tiba khawatir.
“Ada masalah apa?” Ayah langsung menggenggam bahu. Beliau lalu melihatku sesaat. Tapi tatapannya sudah berbeda.
“Datang saja ke rumah setelah Isya. Ini ada kaitannya dengan Rini, Bahar,” ucap Angku Badri berbisik.
Ayah mengangguk-seketika langsung paham sebelum angku Badri pulang.
“Ada apa dengan angku Badri, pak?” tanyaku duduk belakang motor.
“Nanti saja Ayah ceritakan,” ketus Ayah seperti merasa terganggu atas pertanyaan yang kuajukan.
Kami lalu tiba di rumah lalu membersihkan badan. Baru beberapa menit di rumah setelah mandi dan berganti pakaian, Ayah langsung pamit kepada Umak agar pergi sebentar ke rumah Angku Badri. Dan Ayah mengambil kunci cadangan andaikan ia pulang tengah malam.
Aku pun ikut pamit ke Umak dengan alasan bermain. Walaupun, alasannya lebih karena penasaran “apa yang akan mereka bahas terkait pembicaraan mereka sebelum pulang tadi?” Rumah Angku Badri berada tak jauh dari surau. Setelah melewati jembatan, lalu belok ke kanan dan di dekat pohon jambu pasir, di situlah rumah beliau berdiri.
“TOKTOKTOK,” ketuk Ayah sekuat-kuatnya.
“BADRII!!.” Ayah berteriak dan mendorong berkali-kali menggoyang gagang pintu. dan tak menghasilkan apa-apa.
Jendela demi jendala kami intip. Tapi, tidak ada yang bisa dicongkel. Sampai akhirnya membawa kami ke belakang rumah. Dan firasatku mulai condong ke hal yang tidak baik.
“Sial, pintu belakang tidak terkunci!”
Pintu depan lalu kubuka. Lalu Ayah masuk dan kujelaskan bahwa pintu belakang tidak terkunci dengan baik. Kami memeriksa ruang tamu dan bilik kamar. Tapi tidak ada angku Badri. Ayah bersandar di dinding memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Napasnya menyatu dengan rasa takut.
“Apa yang sebenarnya terjadi, Yah?” tanyaku.
“Kita terlambat. Kita terlambat, Nak,” ucap Ayah. “Rido. Ini pasti ulah Rido.” Mulut Ayah bergetar.
“Siapa Rido?” tanyaku lagi.
“Anak mereka,” jawab Ayah dengan lirih.
“Bukankah mereka tidak punya anak, Yah?” bantahku.
“Ya. Rini memang tidak mengakui anaknya.”
Layar pun tersingkap. Tahun demi tahun, rahasia akhirnya terungkap. Mereka berdua pindah bukan karena nasib, tetapi karena kawin lari.
Disebabkan atas nama cinta yang menggebu-gebu, Rini meminta kejelasan terkait kehamilan. Badri waktu itu hanya mengiyakan. Mereka sepakat untuk meninggalkan putranya di rumah sakit. Tanpa berpikir lama, dengan membawa sedikit harta dan dosa. Mereka memutuskan pergi dari kampung halaman. Badri baru menceritakan ini kepada Ayah pasca sepeninggal istrinya. Setelah itu baru kami sadar, kenapa Rini bisa jatuh sakit sebelum meninggal. Serangan jantung.
“Tolong ambilkan air, Nak,” kata Ayah yang sepertinya ingin menenangkan pikiran. Aku tahu, air memang sangat manjur saat seorang gelisah.
“Kamar mandinya dimana, Yah?” tanyaku.
“Lihatlah di sekitar dapur!”
Dengan mempercepat langkah. Pintu kayu setengah lapuk kubuka. Ikan yang tadi diberikan belum selesai dibersihkan. Dan pisau cutter tergeletak di dekat dinding sumur. Mendapati di ember pun tidak ada air yang cukup. Aku menimba beberapa ember untuk melanjutkan membersihkan ikan. Dan setelah itu kubawa air untuk Ayah.
**
“CIHHK, itu saja, Pak Jorong?” sela Hendra.
“Ya, Begitulah. Tapi ada yang aneh, Hendra…”
Hendra diam membisu lagi. Menunggu jawaban.
“Air yang kudapati ternyata bercampur darah. Lalu keesokannya, setelah subuh, Ayahku mengumumkan berita kemalangan Angku.”
“Ceritamu tidak cukup untuk mengurungkan niatku, Pak Jorong. Begini saja, kutambahi lima puluh juta lagi. Bagaimana?”
“Bagaimana pun tawaranmu tak bisa kuterima, Hendra. Kalau masalah uang. Aku sudah lama meninggalkannya. Anakku sudah merantau semua. Adapun istriku, sudah kembali ke rumah ibunya. Aku tidak punya siapa-siapa di sini.”
Seketika Hendra menegakkan punggungnya. Lalu pamit, tanpa basa-basi. Dan gelas kopinya belum habis.
“Aku akan datang seminggu lagi, Pak Jorong,” katanya setelah membunyikan engkol motor Rx Kingnya. Cukup mengganggu telinga.
“Aku sudah bukan jorong lagi, Hendra. Tapi, tunggu dulu. Kenapa harus menunggu hingga seminggu? Apa yang kau inginkan?”
Hendra melumat sisa tembakaunya dengan kaki kanannya.
“Sederhana. Aku hanya butuh sedikit bukti, jika dalangnya ada di sekitar sini.”
“Dalang? Siapa?”
Sontak bulu kudukku merinding. Tapi, dia seenaknya pergi tanpa memberi tahu siapa dia sebenarnya.

 3 months ago
46
3 months ago
46