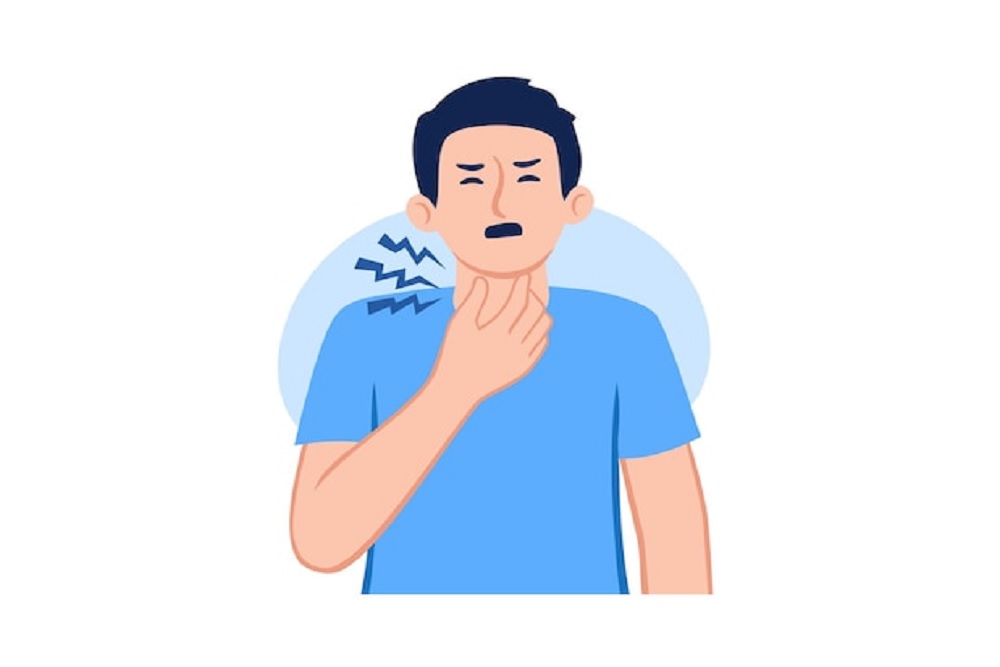Saya tidak pernah menyangka bahwa malam yang saya lewati pada 20 November itu akan berubah menjadi awal dari sebuah nestapa panjang. Hujan turun dengan deras, seolah langit menyimpan sesuatu yang ingin diungkapkannya, tetapi bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk peringatan yang pedih. Saat pesawat mendarat di BIM, saya masih menganggap itu hanya hujan biasa, hujan penghujung tahun. Saya salah besar. Hujan itu bukan hujan musiman; ia adalah awal dari sebuah murka alam yang sejak lama ditahan oleh hutan-hutan yang kini tak lagi ada.
Hari-hari berikutnya, 21, 22, 23, hingga 25 November, Sumbar, Sumut, dan Aceh ditempa hujan tanpa jeda, bagai dunia yang sedang menangis. Langit redup dan berat, udara basah oleh kecemasan. Saya sempat merasa aman di rumah saya di Cupak Tangah, Pauh. Komplek saya tidak lagi banjir karena program bersih-bersih saluran yang dicanangkan Camat Pauh. Betapa sebuah kerja kecil penuh niat baik ternyata mampu menyelamatkan satu kawasan. Tapi ketenangan itu rapuh, sangat rapuh sebab jauh di luar sana, tanah yang kehilangan penjaganya mulai menyerah pada amuk alam.
Tanggal 26 November, berita buruk mulai berdatangan: longsor di sana, sungai meluap di sini. Namun tanggal 27 adalah hari ketika duka itu menampakkan wajahnya yang paling kejam. Bukan hanya air yang datang, tapi gelondongan kayu-kayu besar, saksi bisu dari pohon-pohon yang dirampas paksa dari lereng-lereng peradaban kita. Kayu-kayu itu seperti tubuh-tubuh yang dipaksa mati dua kali: pertama ketika ditebang oleh manusia yang tamak, kedua ketika menghantam rumah dan manusia tak bersalah di bawahnya. Jembatan di Gunung Nago hanyut; rumah-rumah di Lubuk Minturun luluh lantak oleh derasnya aliran air bercampur lumpur dan serpihan hutan yang hilang.
Tidak ada lagi yang bisa menahan badai itu. Sebab apa yang seharusnya menjadi tameng alam, akar pepohonan, rimbun hutan, tanah yang padat, semua telah diperkosa oleh tangan-tangan rakus yang diselimuti alasan “investasi” dan “pembangunan”. Dan mereka tidak sendiri, di belakang mereka ada kekuatan gelap yang namanya tidak pernah muncul di berita, tapi kuasanya menembus meja rapat, kantor perizinan, hingga hutan paling sunyi. Kekuasaan antah-berantah yang lebih memilih keuntungan daripada kemanusiaan.
Puncaknya datang pada 28 November. Jalan Padang–Bukittinggi putus total, rumah-rumah sepanjang Batang Kuranji tersapu bersih, jalan Soekarno-Hatta berubah menjadi sungai lumpur tebal. Kota Padang seperti sedang memikul dosa yang bukan dibuat oleh rakyatnya.
Dan di tengah kekacauan itu, saat shalat Jumat. Dalam sujud yang paling lama, saya memohon agar Allah mengakhiri cobaan ini. Saya mohon dalam suara yang tidak bisa saya ucapkan, hanya bisa saya titipkan pada detakan jantung yang gemetar. Dan ketika sore datang, langit tiba-tiba terlihat cerah. Awan hitam mundur perlahan. Malamnya bulan tujuh hari bulan rabi’ul akhir 1447 H muncul dengan tenang, seolah alam baru saja meletakkan sebuah cermin besar di hadapan kita semua, memaksa kita melihat diri kita sendiri.
Tetapi yang paling menyakitkan bukanlah hujannya. Bukan anginnya.
Bukan sungainya yang meluap. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa musibah ini bukan semata-mata takdir, ini adalah akibat dari keserakahan manusia.
Betapa pedih hati ini ketika membayangkan: Anak-anak yang kini menjadi yatim,
ibu-ibu yang kehilangan tempat berpulang, keluarga yang rumahnya hanyut bersama kayu-kayu yang dulu berdiri gagah sebagai pelindung bumi,
para petani yang sawahnya hilang ditelan lumpur pekat.
Alam hanya melakukan apa yang alam lakukan ketika ia dikhianati. Dan kepada para pembalak, kepada para pengusaha yang menghalalkan segala cara, kepada para pejabat yang menutup mata dan telinga, kepada kekuatan antah-berantah yang bersembunyi di balik kursi jabatan: inilah harga dari pengkhianatan kalian.
Tetapi yang membayar bukan kalian. Yang membayar adalah kami, rakyat biasa yang selalu diingatkan untuk menjaga lingkungan, yang selalu diminta mematuhi aturan, yang diajarkan agar tidak merusak alam. Kami telah melakukan bagian kami, kami telah menjaga, membersihkan, merawat, dan mematuhi. Tetapi apa arti semua itu jika di atas sana, di ruang-ruang yang dingin dan penuh kepentingan, pengkhianatan terhadap bumi dilakukan dengan senyum dan tanda tangan?
Kini kami hidup dalam luka yang tidak kami ciptakan. Maka dengarkanlah ratap kami ini, ratap dari tanah yang tercabik-cabik oleh tangan manusia yang tak kenal belas kasihan. Ratap dari bumi Minangkabau yang menangis bukan hanya karena hujan, tetapi karena dikhianati oleh anaknya sendiri.
Semoga musibah ini menjadi peringatan yang menggetarkan hati, bukan hanya bagi rakyat kecil yang sudah cukup menderita, tetapi bagi mereka yang selama ini merasa tak tersentuh oleh hukum alam ataupun hukum manusia. Mereka yang selalu menyalahkan cuaca ekstrim sebagai penyebab.
Karena pada akhirnya, alam tidak pernah lupa. Ia hanya menunggu. Dan ketika ia menegur, ia menegur dengan cara yang membuat seluruh bumi bersaksi.
Dr. Abdul Aziz
Dosen FEB Universitas Andalas

 3 months ago
35
3 months ago
35