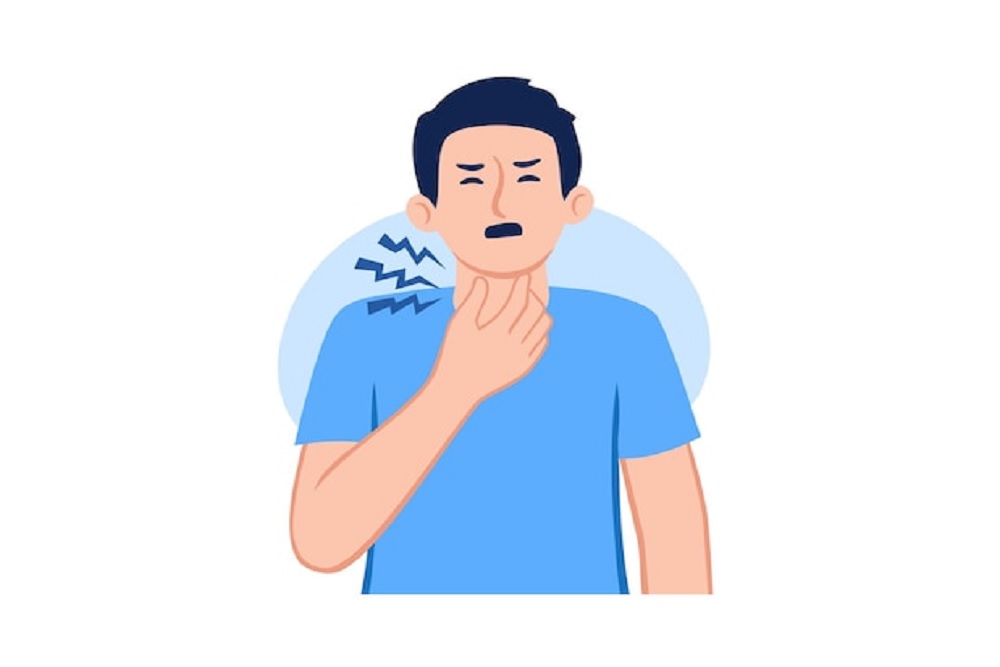“PUKIMAK, LAH!” Suara teriakan yang disertai bunyi berdebum mengejutkanku. Sebuah pukulan kuat ke meja dan diiringi bunyi lain yang mengganggu. Herannya, sepertinya hanya aku yang merasa terganggu. Malah, lawannya tertawa-tawa, kemudian menghitung angka yang aku sendiri tidak paham maknanya.
“Empat belas:dua.”
“Kau yang kocok!”
Kemudian bunyi yang menggangguku—bunyi batu domino yang beradu—kembali memenuhi warung kecil ini. Suasana hiruk-pikuk ini sungguh membuatku tidak nyaman; bunyi kendaraan lalu-lalang di jalan, gelak-tawa para lelaki paruh baya, serta suara lelaki lainnya yang asyik menelpon. Bunyi itu saling beradu membuat ingar-bingar memenuhi kepalaku. Andai saja bos lamaku menggunakan otak, tentu aku tidak akan berontak hingga berakhir pada pemutusan kontrak. Andai juga bos lamaku punya hati, tentu aku tidak berhenti, dan terjebak kini bersama para lelaki busuk ini.
“Kenapa?” Sebuah tepukan lembut di pundakku. Boco yang tadi ikut bermain domino, kali ini duduk di sampingku. Gilirannya sudah habis dan digantikan orang lain.
“Sudah selesai mainnya?”
“Sudah. Aku kalah gara-gara salah pilih mandan.” Mulutnya dimonyongkan ke arah pria yang berisik tadi. Tentu saja si pria berisik itu tidak terima.
“Kau yang bodoh. Sudah kukasih jalan masih juga balak lima dan balak enam tertimbun. Macam pemula.”
“Mana pula. Justru langkahku mati karena Abang tak pandai main menghitung batu.”
Mereka saling bersitegang, membuatku menyesal bertanya, meskipun hanya basa-basi. Untunglah Ocol datang menyelamatkanku dari situasi canggung ini.
“Sudah, yang kalah, ya kalah aja. Pokoknya makan dan rokok hari ini kalian yang bayar,” ujarnya sambil mengerling padaku, “ayo, pesan minum lagi.”
Aku tersenyum. Tentu saja aku tidak ikut memesan minum setelah tahu bahwa semua akan dibayar oleh si pria berisik itu. Muka kotak, pendek, perut buncit, dan banyak lagak, setidaknya itu kesan pertamaku mengenalnya. Namun sebagai seorang anak baru, kusalami dan kuperkenalkan diri sebagai junior yang sopan.
Damai, demikian ia bernama. Mungkin ketika dulu mau memberi nama, orang tuanya sudah bisa meramalkan bahwa anaknya akan menjadi tukang ribut, sehingga menamainya Damai dengan harapan ia bisa menjadi juru damai.
“Kenapa kau melamar bekerja di sini? Ini hari pertamamu, kan?”
Aku mengangguk. Sebenarnya aku malas mengulang untuk kesekian kali. Tadi—sebelum dibawa Boco ke sini—ketika perkenalan karyawan baru, dan ketika duduk di pantry, bahkan ketika merokok di parkiran kantor; setidaknya sudah lima kali kujelaskan kenapa aku memilih berhenti sebagai supervisor di sebuah mal dan malah melamar kerja di sini. Kujawab saja dengan enggan, “Kontrakku di perusahaan lama tidak diperpanjang.”
“Jadi, bagaimana menurutmu?”
“Apanya?”
Ia mendengkus kesal. Dengan gaya tengil ia mengambil rokok Boco, menyalakannya, kemudian berkata, “Ya, bagaimana menurutmu di sini? Santai, kan? Tentu di tempat kerja lamamu tidak sesantai di sini.”
“Yah, cukup kaget, sih.” Aku tertawa garing.
“Kaget gimana?”
“E-em. Jujur, sebenarnya aku merasa agak tertipu. Aku melamar posisi sebagai junior relationship officer. Kupikir sebagai staf humas atau HRD. Rupanya setelah diterangkan, pekerjaannya sebagai penagih utang. Tahu begitu, kulamar sebagai surveyor saja seperti Bang Ocol.”
Damai terkikik melihatku tersenyum kikuk. Namun kemudian kulanjutkan dengan serius, “Aku ingat dulu ibuku sering sembunyi di bawah kasur dan menyuruhku mengatakan beliau tidak di rumah jika ada yang mencari. Sekarang, justru aku menjadi penagih utang. Ironis.”
Boco menepuk kembali pundakku. Dengan muka serius, ia berkata, “Kau tahu … kau itu terlalu naif. Coba kau lihat ini,” ia mengeluarkan sebuah kertas yang tadi di-print-nya di kantor dan pada beberapa bagian diwarnai menggunakan stabilo, “ini bucketlist punyaku. Yang kustabilo ini, OSAR-nya besar. Kau lihatlah. Orang miskin mana yang punya utang ratusan juta? Utang ibumu tentu tidak bisa dibandingkan dengan mereka.”
Kupandang kertas berisikan tabel dan angka-angka yang membuat kepalaku pusing.
“Mereka itu orang kaya, Bro. Jika kau tahu penghasilan mereka, mungkin kau menangis membandingkan gajimu yang tidak seberapa dengan mereka.” Ocol menambahkan penjelasan bahwa kredit hanya akan disetujui jika penghasilan serta serta laporan BI checking calon debitur dianggap tidak bermasalah.
“Ya, meskipun ada juga orang kaya baru yang kebanyakan gaya,” tambah Damai sembari menceramahiku mengenai pengalamannya selama menjadi debt collector.
“Intinya, jangan kau pandang rendah pekerjaan ini hanya karena tidak di ruangan ber-AC. Malah, di sini kau bisa mencari pemasukan lain dengan menjadi makelar mobil. Percayalah, mencari uang di sini, gampang. Di sini kerjanya santai. Masuk kantor, absen, terus ngopi. Kerjanya cuma dua minggu terakhir setiap bulannya saja. Kau cukup pastikan agar tidak ada customer-mu yang flow ke 31-60 (hari). Terus, pastikan OSAR (utang pokok) dari total customer-mu tidak melebihi target OSAR yang diberikan pimpinan. Caranya bagaimana, ya kau kejar customer yang memiliki utang pokoknya besar, atau yang hampir flow. Sesederhana itu. Ini semua tentang seni, Bro. Seni bernegosiasi dan memenangkan pertarungan tanpa pertarungan.”
“Kalau customer menggertak bagaimana, Bang?”
“Kau tahu anjing yang menggongong? Kira-kira serupa itulah mereka. Mereka tidak akan berani menyerang. Jangan takut. Sebelum mereka menggertak, kita gertak duluan.”
“Berarti kita harus duluan menjadi anjing yang menggongong?”
“Anjing!” makinya sambil menggaruk kepala, “maksudku, kau jangan kena mental. Dulu aku pernah dikejar customer menggunakan parang. Bukannya lari, malah kutantang. Kubilang, ‘Kalau berani, letak parangmu. Kita main one by one.’ Ia ciut, kemudian minta maaf.”
Damai membusung dan menepuk dadanya. Bibirnya mencibir, “Pada dasarnya, mereka takut sama kita. Ibarat anjing terjepit. Di satu sisi menjerit, di satu sisi mau menggigit. Tapi, customer itu salah orang jika berlaku seperti anjing kepadaku. Belum tahu dia siapa aku. Aku ini Damai. Aku cinta perdamaian. Tapi pantang bagiku untuk lari,” pungkasnya sambil menyesap kopi, mengeluarkan bunyi “ah”—yang seakan-akan, mengopi tidak lengkap tanpa desah.
Damai masih saja bercerita tentang keberaniannya. Ia sering ke luar kota sendirian dan pulang membawa uang tunai ratusan juta yang disimpannya di dalam tas, hasil pembayaran utang debitur yang menunggak. Tak jarang pula ia berhasil membawa mobil tarikan.
Seakan ingin membuktikan ucapannya, Damai mengajakku ke tempat customer-nya, “Kau ikut aku, ya. Kutunjukkan bagaimana caranya menarik unit.”
Aku hendak menolak. Tidak ada alasan kuat bagiku untuk mengikutinya—kau tahulah, ini hari pertamaku bekerja. Terlalu cepat rasanya jika aku sudah harus menarik mobil. Ditambah lagi aku tidak begitu menyukai Damai, terlebih caranya bicara itu. Namun Boco dan Ocol menyarankan untuk ikut.
“Ikut saja, sambil kau bisa belajar bagaimana cara Bang Damai bernegosiasi,” kata Ocol yang diamini Boco.
“Pokoknya, nanti kalau mobilnya berhasil kita tarik, kau bawa motorku. Biar aku yang bawa mobilnya.”
“Oke.”
Sepanjang jalan sejak kami meninggalkan warung, Damai tidak berhenti bercerita, sedangkan aku hanya diam mendengarkan. Untungnya, suaranya banyak terbawa angin dan bercampur dengan bunyi dengung mesin motor tuanya sehingga aku tidak perlu mendengarkan bualannya.
“Bagaimana jika nanti customer menolak menyerahkan unit?” Aku berteriak di kupingnya.
“Kita dilindungi Undang-Undang Fidusia. Jangan takut. Lagipula, si bajingan ini sudah menunggak dua bulan, dan selalu berkilah, bahkan sempat menghilang. Tadi malam aku dapat informasi kalau dia sudah di rumah. Ini sudah keluar surat penarikan unit,” balasnya dengan teriakan bercampur liur yang memercik ke wajahku.
Aku mual mencium aromanya. Cuaca terik, debu, dan bising di jalan semakin membuatku muak. Suasana semakin panas ketika Damai memaki pelanggan kami di rumahnya sendiri—seorang lelaki paruh baya yang kurus, berambut putih dan bermata sayu—dengan berapi-api.
“Utang pokok Bapak masih besar, baru sepuluh kali bayar. Bukannya dibayar, malah menghilang. Bapak punya otak?”
Si pelanggan menunduk, dan Damai semakin menekan, “Unit mana? Bapak jual?”
“Ada. Di belakang.”
“Ini. Silakan dibaca,” tegasnya sambil menyerahkan surat tugas, “unit kami tarik.”
“Tolonglah, Pak. Kali ini saja. Bantu saya, Pak. Usaha saya sedang sepi. Pasti saya bayar. Saya janji,”
Si pelanggan memelas, namun Damai tidak hendak berdamai.
“Pak … kalau janji bisa dipegang, tentu wakil rakyat, presiden, dan pejabat-pejabat tidak akan korupsi.”
Si pelanggan diam.
“Kami sudah sangat berbaik hati. Begini saja, sekarang giliran Bapak yang bantu kami. Serahkan dulu unitnya. Nanti bisa ditebus kalau ada uang.”
Si pelanggan berdiri. “Tunggu sebentar. Saya ke belakang dulu,” katanya sambil berlalu. Langkahnya gemetar. Entah karena apa, aku teringat pada novel Karl May: Dan Damai di Bumi! Sayangnya, Damai yang bersamaku tidak mencerminkan damai pada novel itu.
Damai mengedipku sambil menyeringai. Setelah si pelanggan menghilang di balik pintu, Damai berbisik, “Kau lihat, kan? Kita harus mempertahankan pressure. Hahaha. Nanti sehabis mengantarkan mobil ke pool, kutraktir kau karaoke—”
Belum selesai Damai berkata, si pelanggan muncul dengan membawa parang di tangan. Ia mengacungkan parang sambil berjalan mendekati kami. Kali ini matanya tidak lagi memelas. Rahangnya mengeras dan tegas. Mulutnya bergetar. Untungnya aku dulu terbiasa menangangi keluhan pelanggan—meskipun tetap tidak terbiasa menangani keluhan pimpinan. Namun, di tempat lamaku bekerja, tidak pernah ada pelanggan yang membawa, alih-alih, mengacungkan parang.
“Tenang, Pak. Jangan gegabah. Semua ada solusi.”
Keringat dinginku bercucuran, sedang cuaca panas berdengkang. Kedua tangan kuangkat membentuk gestur mendorong, mengajukan solusi perdamaian. Damai harus bisa membujuk si pelanggan untuk berdamai. Ketika kulirik ke arahnya, Damai sudah berada di atas motor tuanya, mencoba mengengkol dengan panik. [*]

 3 months ago
36
3 months ago
36