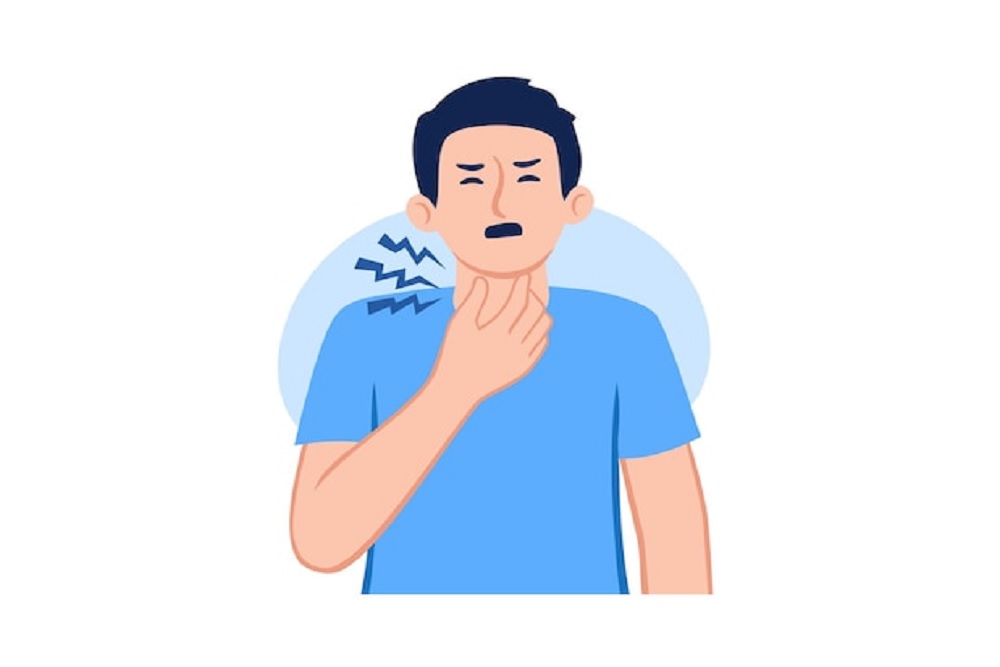Oleh Muh. Syahrul Ago, Dosen Universitas Bosowa
KabarMakassar.com — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung atau Pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke ruang publik setelah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pidatonya di peringatan ulang tahun ke 60 Partai Golkar yang membuka peluang Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
Kemudian dalam pidato selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto turut merespon Pernyataan Ketum Golkar bahwa perlunya dilakukan peninjauan sistem pemilu khususnya pemilihan kepala daerah, meninjau kembali pilkada langsung dengan alasan efisiensi anggaran, bahkan mencontohkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India misalnya yang pemilihan kepala daerahnya melalui lembaga perwakilan daerahnya masing-masing.
Hal ini tentu menghidupkan kembali perdebatan lama yang sejatinya belum pernah benar-benar padam. Namun, wacana ini tidak sesederhana soal biaya. Pilkada bukan semata-mata agenda teknokratis, melainkan menyangkut arah demokrasi, sistem ketatanegaraan, dan relasi kekuasaan antara rakyat, DPRD, dan pemerintah daerah.
Pertama, pilkada tidak langsung berpotensi mencederai sistem presidensial yang dianut Indonesia. Dalam sistem presidensial, legitimasi kekuasaan eksekutif berasal langsung dari rakyat.
Ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, relasi tersebut bergeser menjadi relasi politik perwakilan yang lebih dekat dengan sistem parlementer. Hal ini berisiko menciptakan ketergantungan kepala daerah kepada DPRD, bukan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Padahal, salah satu semangat utama reformasi 1998 adalah mengembalikan kedaulatan itu secara langsung kepada rakyat, termasuk dalam memilih pemimpinnya di daerah.
Pemberian contoh negara tetangga seperti Malaysia dan India sepertinya belum tepat karena memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan Indonesia.
Kedua, fungsi pengawasan DPRD justru berpotensi melemah atau bahkan terlalu kuat sehingga pelaksanaan program-program pemerintah di daerah menjadi tidak efektif. Artinya tidak terjadi keseimbangan kekuasaan antara lembaga perwakilan dan pemerintah.
Dalam teori checks and balances, pengawasan yang efektif mensyaratkan adanya keseimbangan kekuasaan antara yang mengawasi dan yang diawasi. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka relasi tersebut berpotensi berubah menjadi relasi “hutang politik”.
Kepala daerah cenderung menjaga kepentingan fraksi atau elite DPRD yang memilihnya. Akibatnya, fungsi pengawasan bisa berubah menjadi kompromi politik, bukan kontrol substantif terhadap kebijakan dan anggaran daerah.
Ketiga, alasan efisiensi anggaran patut dipertanyakan. Namun, mahalnya demokrasi saya kira tidak bisa dijawab dengan mengurangi partisipasi rakyat.
Lebih jauh kita harus berfikir bahwa pilkada oleh DPRD bukan jaminan lebih murah atau lebih efisien. Tetapi, praktik politik transaksional, lobi elite, dan potensi “mahar politik” justru berisiko memindahkan biaya dari ruang publik ke ruang gelap yang sulit diawasi dan diukur.
Artinya, mahalnya biaya politik harus diklarifikasikan dalam dua hal, apakah mahal dari aspek biaya pelaksanaan pilkadanya atau mahal dari aspek biaya kampanye atau bahkan politik uangnya. Justru pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sedikit banyaknya mempunyai hubungan emosional pada saat pelaksanaan kampanye.
Keempat, apabila lahir regulasi (UU) tentang perubahan sistem pilkada, maka dapat dipastikan memicu gelombang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Apalagi MK melalui sejumlah putusannya telah menegaskan bahwa makna demokrasi Indonesia bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan adil. Mengubah sistem pilkada tanpa landasan konstitusional yang kuat justru akan menambah ketidakpastian hukum dan konflik norma.
Kelima, sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami pilkada tidak langsung sebelum reformasi, dan praktik tersebut sarat dengan sentralisasi kekuasaan serta minim akuntabilitas.
Perubahan menuju pilkada langsung bukanlah keputusan emosional, melainkan respons atas pengalaman panjang penyalahgunaan kekuasaan di daerah. Jika hari ini sistem itu hendak diubah kembali, pertanyaannya sederhana: apa masalah mendasar pilkada langsung yang tidak bisa diperbaiki tanpa harus memundurkan demokrasi?
Keenam, pilkada oleh DPRD memang tampak lebih sederhana bagi partai politik. Namun kesederhanaan prosedur tidak selalu sejalan dengan kualitas demokrasi. Justru dalam skema ini, potensi intervensi pemodal besar dan kelompok kepentingan semakin terkonsentrasi.
Pengusaha atau aktor berduit yang memiliki kepentingan, cukup “mengamankan” suara elite DPRD, bukan lagi meyakinkan jutaan pemilih. Dampaknya, kebijakan publik berisiko semakin elitis dan jauh dari kepentingan masyarakat luas.
Alih-alih menghapus pilkada langsung, yang dibutuhkan adalah perbaikan serius: penguatan pengawasan dana kampanye, pengetatan sanksi politik uang, serta profesionalisasi penyelenggara pemilu. Demokrasi memang mahal, tetapi jauh lebih mahal jika kita harus membayar ongkos kemunduran demokrasi itu sendiri.
Wacana pilkada tidak langsung seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan jalan pintas. Efisiensi anggaran penting, tetapi kedaulatan rakyat jauh lebih fundamental. Indonesia tidak kekurangan pengalaman tentang apa yang terjadi ketika suara rakyat dikecilkan atas nama stabilitas dan efisiensi. Sejarah telah memberi pelajaran, tinggal apakah kita mau belajar darinya atau mengulanginya kembali.