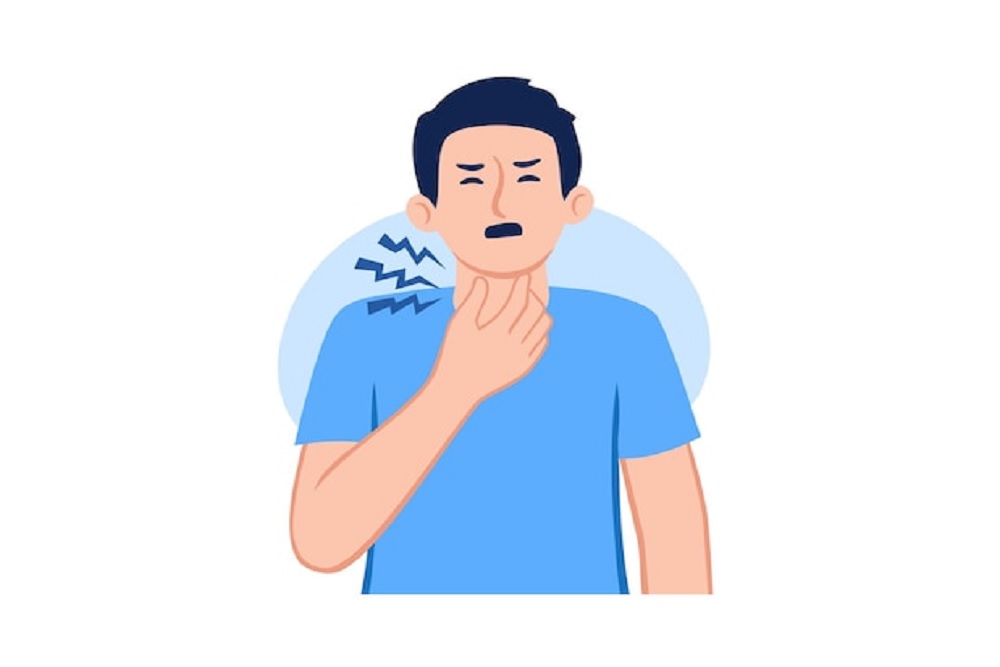KabarMakassar.com — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan resmi mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka menilai perluasan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berpotensi menabrak prinsip-prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara.
Permohonan tersebut diajukan oleh lima organisasi masyarakat sipil dan tiga warga negara, masing-masing yakni Imparsial, YLBHI, KontraS, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan LBH APIK Jakarta, serta warga bernama Ikhsan Yosarie, Mochamad Adli Wafi, dan Muhammad Kevin Setio Haryanto.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 digelar di Gedung MK, Jakarta, Selasa (04/11).
Dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK membatasi peran militer dalam urusan sipil dan keamanan siber, yang dinilai berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi.
Kuasa hukum para pemohon, Andrie Yunus, menegaskan sejumlah pasal dalam UU TNI yang diubah tahun 2025 justru memperluas kewenangan TNI di ranah sipil, termasuk dalam penanganan pemogokan, konflik sosial, hingga urusan pemerintahan daerah.
“Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU TNI memberi ruang bagi TNI untuk membantu tugas pemerintahan di daerah, termasuk menangani konflik komunal dan pemogokan. Ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat secara damai,” jelas Andrie.
Menurutnya, pasal tersebut berpotensi digunakan untuk melegitimasi keterlibatan militer dalam urusan sipil, termasuk menangani unjuk rasa atau aksi buruh, padahal pemogokan merupakan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang dan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 yang telah diratifikasi Indonesia.
“Keterlibatan TNI dalam menangani konflik sipil dan pemogokan buruh mengaburkan batas antara keamanan negara dan keamanan masyarakat sipil. Ini berbahaya bagi demokrasi,” ujar Andrie dalam persidangan.
Koalisi juga menilai istilah ‘konflik komunal’ dalam pasal tersebut tidak memiliki batasan hukum yang jelas, sehingga membuka peluang penyalahgunaan kekuatan militer di ranah sipil. Mereka menilai rumusan tersebut menyimpangi sistem hukum konflik sosial yang sudah diatur dalam undang-undang lain.
Selain soal urusan sipil, para pemohon juga menyoroti Pasal 7 ayat (2) angka 15 yang memberikan TNI kewenangan membantu menanggulangi ancaman pertahanan siber.
Menurut Koalisi, tugas tersebut tidak tepat karena aspek keamanan siber bukan bagian dari OMSP, melainkan fungsi pertahanan nasional dalam konteks operasi militer perang (OMP).
“Pasal ini keliru menempatkan peran militer dalam ranah yang seharusnya dikelola oleh lembaga sipil seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Frasa ‘membantu menanggulangi ancaman pertahanan siber’ sangat lentur dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum,” jelas Andrie.
Ia menilai perluasan makna “pertahanan siber” berisiko memperluas keterlibatan TNI dalam pengawasan data dan aktivitas digital warga, padahal ranah tersebut tidak berkaitan langsung dengan pertahanan negara dari ancaman luar.
“Kalau ruang ini tidak dibatasi, bisa saja militer ikut campur dalam pengelolaan keamanan siber yang menyangkut privasi publik. Ini bisa mengarah pada pengawasan berlebihan,” ujarnya.
Koalisi juga menilai mekanisme pelaksanaan OMSP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) tidak seimbang secara politik karena Presiden diberikan kewenangan penuh tanpa mekanisme pengawasan DPR.
Padahal, menurut mereka, pelibatan TNI dalam urusan sipil seharusnya disertai mekanisme kontrol politik dan hukum sebagaimana pelaksanaan operasi militer perang (OMP).
“Keterlibatan DPR menjadi bentuk pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. OMSP seharusnya juga berada di bawah pengawasan lembaga legislatif,” kata Andrie.
Koalisi menilai ketentuan yang terlalu luas ini bisa digunakan untuk mengerahkan TNI dalam urusan non-pertahanan, seperti keamanan dalam negeri, demonstrasi, dan kegiatan sipil lainnya, tanpa dasar hukum yang kuat.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur meminta pemohon memperjelas pasal mana saja yang secara langsung dianggap merugikan hak konstitusional warga.
“Tidak perlu semua pasal disebutkan, cukup fokus pada yang benar-benar menimbulkan pelanggaran hak,” ujar Ridwan.
Sementara Hakim Arsul Sani menekankan perlunya kejelasan kedudukan hukum pemohon, baik sebagai badan hukum maupun individu. Ia juga mengingatkan agar permohonan disesuaikan dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.
Adapun Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar pemohon memperkuat uraian hubungan sebab-akibat antara pasal yang diuji dan kerugian konstitusional yang dialami.
“Misalnya soal pertahanan siber, bagaimana keterlibatan TNI di bidang itu merugikan hak para pemohon? Hal ini penting agar bisa masuk ke pokok perkara,” tegas Saldi.
MK memberikan waktu 14 hari kepada Koalisi Masyarakat Sipil untuk menyempurnakan permohonan mereka. Naskah perbaikan harus diserahkan paling lambat 17 November 2025 pukul 12.00 WIB ke Kepaniteraan MK.
Sidang lanjutan akan digelar dengan agenda mendengarkan pokok perbaikan permohonan dari para pemohon.
Dengan permohonan ini, Koalisi Masyarakat Sipil berharap Mahkamah Konstitusi dapat memperjelas batas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil, serta memastikan bahwa TNI tidak digunakan dalam ranah non-militer yang seharusnya menjadi kewenangan lembaga sipil.
“Kami ingin memastikan supremasi sipil tetap terjaga. Kekuatan militer harus dibatasi sesuai konstitusi, bukan diperluas ke ranah sosial, politik, dan digital,” tutup Andrie Yunus.