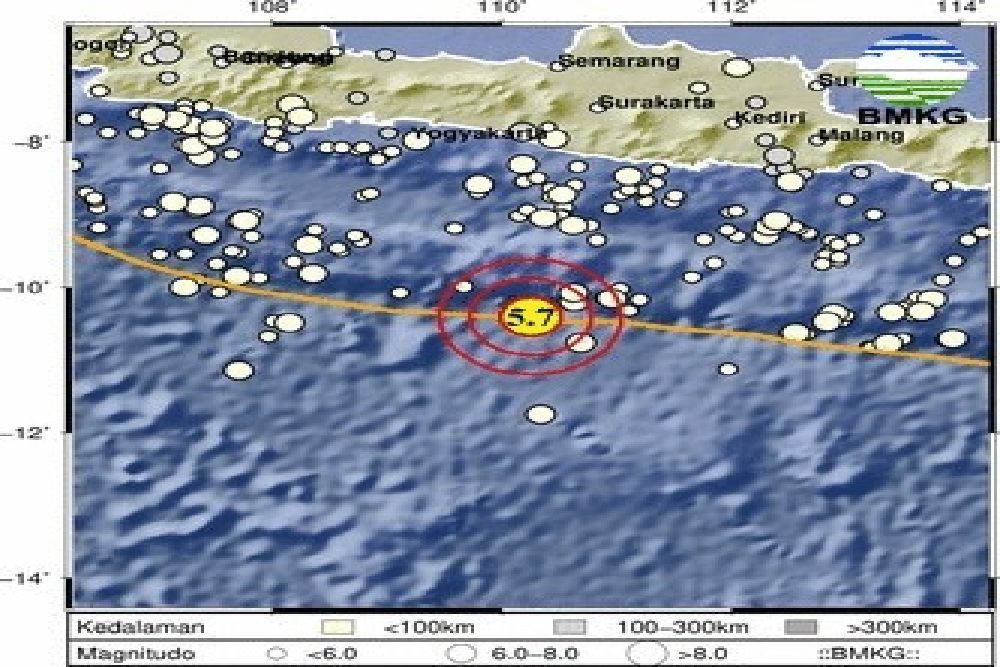KabarMakassar.com — Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Selatan untuk periode 2025–2029 didesak untuk lebih inklusif terhadap kelompok marjinal.
Desakan ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk ‘Membaca Visi, Permasalahan, dan Prioritas Pembangunan Sulsel 2025–2030’ yang digelar dalam rangka Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kantor DPW PKB Sulsel, Minggu (19/7).
Apalagi setelah Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Setiawan Aswad, memanfaatkan forum politik tersebut untuk mengungkap secara terang-terangan gagalnya penyelesaian 18 masalah strategis dalam RPJMD Sulsel periode 2020–2024.
Kordinator Program MAMPU Yayasan BaKTI, Lusia Palulungan, menyoroti masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, berbagai persoalan yang menimpa kelompok ini justru kerap luput dalam praktik pembangunan, meskipun telah disebutkan dalam dokumen prioritas daerah.
“Isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, keterbatasan air bersih, dan akses pendidikan sangat berdampak pada kaum marjinal. Tapi dalam praktiknya, mereka sering diabaikan. Bahkan pemerintah belum punya data akurat soal jumlah penyandang disabilitas, apalagi jenis ragam disabilitasnya,” ujar Lusia.
Ketiadaan data tersebut, lanjut Lusia, berdampak langsung pada minimnya pelayanan yang tepat sasaran. Ia mencontohkan kebijakan penyediaan layanan kesehatan yang cenderung menyamaratakan akses, seakan-akan semua orang bisa langsung datang ke puskesmas atau rumah sakit.
“Pemerintah mengira semua orang bisa datang sendiri ke layanan kesehatan. Padahal banyak kelompok disabilitas yang tidak bisa mengaksesnya karena hambatan fisik dan sosial. Tanpa data, kita hanya menebak-nebak kebutuhan mereka,” tegasnya.
Yayasan BaKTI juga mencatat sejumlah tantangan serius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Beberapa kabupaten/kota di Sulsel telah memiliki kebijakan terkait pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, namun implementasinya jauh dari kata ideal. Salah satu kendala adalah tidak tersedianya guru pendamping khusus.
“Di banyak sekolah, anak-anak disabilitas tidak mendapat pendamping. Kebijakan inklusi hanya sebatas formalitas. Bahkan di perguruan tinggi seperti Unhas, dari 6.000 pendaftar dengan disabilitas, hanya sekitar 600 yang diterima,” ungkap Lusia.
Selain itu, infrastruktur pendidikan juga masih belum ramah disabilitas. Banyak sekolah memiliki tangga tanpa akses landai atau ramp, yang secara otomatis menyingkirkan anak-anak penyandang disabilitas dari lingkungan pendidikan.
Isu lain yang turut disorot adalah masih tingginya angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Fenomena ini memiliki dampak multidimensi, mulai dari kematian ibu, kemiskinan antargenerasi, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
“Angka kematian ibu yang tinggi salah satunya disebabkan oleh pernikahan usia anak. Anak usia 15 tahun belum siap secara fisik dan psikologis. Ini harus menjadi perhatian serius dalam RPJMD,” ujar Lusia.
Ia juga menyoroti lonjakan kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) baik di tingkat provinsi maupun Kota Makassar, 80 persen kasus yang ditangani merupakan kekerasan terhadap anak, dan dari jumlah itu, 60 persen adalah kekerasan seksual.
“Ini angka yang mengerikan. Kalau tidak salah saya dengar dari kementrian Kalau ada wacana penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk unit layanan perlindungan, maja ini akan menggangu pelayanan yang ada,” kritik Lusia.
Menurutnya, upaya efisiensi anggaran tidak bisa menjadi alasan untuk menyingkirkan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Negara, kata dia, tidak boleh abai dalam situasi darurat kekerasan.
“Kalau DAK dihapus, bagaimana nasib UPTD PPA? Kita tidak bisa bilang ke korban: ‘Tunggu dulu sampai anggaran cair.’ Itu bukan pendekatan kemanusiaan,” tegasnya.
Dalam hal ketenagakerjaan, Lusia mendorong agar Pemerintah Provinsi Sulsel segera membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) seperti yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan nasional ketenagakerjaan inklusif.
“Kalau kita ingin menekan angka pengangguran, kita harus tahu dulu berapa penyandang disabilitas usia kerja di Sulsel. Tanpa data, semua kebijakan hanya retorika,” tambahnya.
Lusia menekankan bahwa pembangunan yang inklusif bukan sekadar jargon, melainkan membutuhkan komitmen politik, anggaran yang memadai, serta keberanian untuk mengubah sistem yang selama ini mengabaikan kelompok marjinal.
Ia menutup dengan menyerukan agar RPJMD Sulsel 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan sosial.
“Jangan lagi kita menulis ‘kesetaraan gender’ dan ‘pemberdayaan disabilitas’ hanya untuk menggugurkan kewajiban. Arah pembangunan lima tahun ke depan harus menjangkau mereka yang selama ini tidak terdengar suaranya,” pungkasnya.